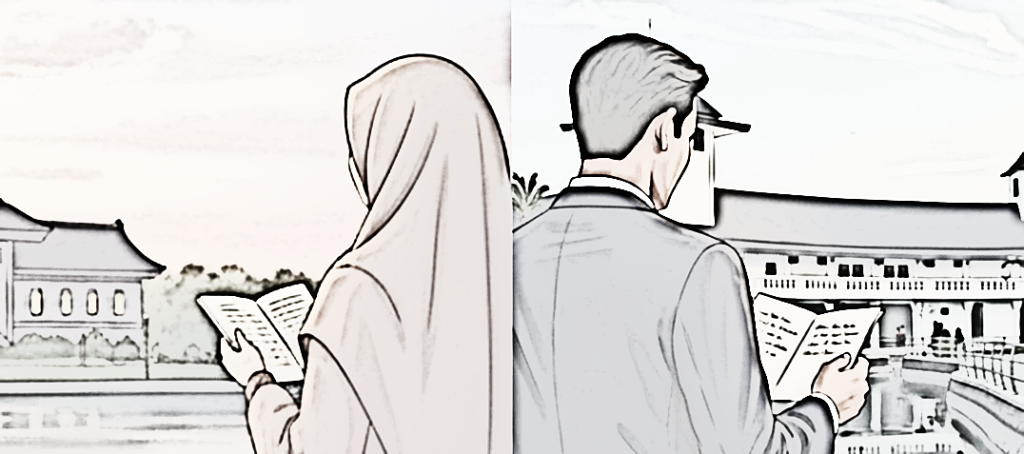
Ada yang berkata: العلم سلطان والحكمة زاد الطريق
Ilmu adalah kekuasaan, dan kebijaksanaan adalah bekal perjalanan.
Tulisan ini lahir dari sosok seorang laki-laki yang pernah mengajariku bukan hanya ilmu nahwu, tapi juga tanpa ia sadari —cara mencintai. Dari setiap bait Alfiyah yang ia uraikan, aku belajar bahwa bahasa dan cinta sama-sama punya qawā‘id, kaidah yang harus ditaati agar tetap indah. Dari sikapnya, aku paham bahwa cinta sejati tidak pernah egois, melainkan bijaksana.
Aku, seorang perempuan yang awalnya hanya kagum pada keluasan ilmunya dan ketenangan bicaranya, pelan-pelan menemukan diriku sedang belajar cinta dengan cara berbeda. Kekaguman itu tumbuh bukan dari manisnya kata-kata, melainkan dari kebijaksanaan yang bersembunyi di balik kalimat sederhana dan kebiasaan kecil yang ia lakukan. Dan perempuan yang menyimpan kagum itu—adalah aku.
Cinta, bagiku, selalu mirip dengan bahasa. Ia bukan sekadar rasa yang meletup-letup, tetapi juga ada aturan yang menuntun. Bahasa Arab bertahan berabad-abad karena para ulama menjaga qawā‘id-nya. Tanpa kaidah itu, kalimat akan kacau, makna runtuh. Begitu pula cinta: tanpa aturan, ia hanyalah luapan perasaan kosong yang mudah hilang arah.
Aku teringat pertama kali belajar tentang dhomir. Cinta itu serupa dhomir dalam ilmu nahwu. Ada dhomir muttashil, yang melekat erat, sederhana, tapi maknanya jelas. Begitulah cinta yang tenang: tidak perlu diumbar, cukup hadir dan terasa. Ada pula dhomir munfashil, yang berdiri sendiri, kadang berlebihan, membuat kalimat mubazir. Bukankah begitu juga cinta? Jika terlalu banyak aksesoris, terlalu banyak kata-kata, ia justru kehilangan kefasihannya. Dari situ aku belajar, cinta paling indah sering kali hadir diam-diam, tanpa berteriak, tapi sampai di hati.
Dalam nadzom Alfiyah, ada bait yang selalu kuingat:
وَفِي اخْتِيَارٍ لاَ يَجِيْءُ الْمُنْفَصِلْ *** إذَا تَــــأَتَّى أنْ يَجِيْءَ الْمُتَّــصِلْ
Bila ada pilihan, jangan datangkan dhomir munfashil,
selama dhomir muttashil memungkinkan untuk dipakai.
Dalam suatu waktu kesempatan yang kita habiskan bersama, ia pernah menasihatiku, “Jangan meminta tolong pada orang lain selama masih bisa kau atasi sendiri. Walau kau tahu orang itu akan mau membantu, bisa jadi di balik wajah lapangnya ia menyimpan letih yang tak pernah kau lihat.” Nasihat itu menancap kuat. Aku sadar, cinta bukan selalu soal membagi lelahku kepadanya, tetapi juga tentang bagaimana aku menjaga agar tidak menambah lelahnya.
Dari sana aku mulai merangkai kaidah.
- Kaidah pertama: cinta tidak membebani. Ia seharusnya menjadi ruang untuk bernapas, bukan beban tambahan.
- Kaidah kedua: cinta tidak berlebihan. Seperti i‘rab, ia harus jatuh di tempat yang pas, tidak lebih, tidak kurang.
- Kaidah ketiga: cinta hadir di posisi yang semestinya, sebagaimana kata menemukan tempatnya dalam kalimat.
- Dan kaidah terakhir, yang tertinggi: cinta sejati adalah cinta yang menuntun pada Allah. Tanpa arah itu, cinta hanyalah bahasa tanpa ruh.
Pelan-pelan aku mengerti, mencintai bukan sekadar perkara merasa. Ia adalah latihan menahan diri, menjaga bahasa, menakar kata, dan memastikan hati tetap fasih meski dalam diam. Karena pada akhirnya, cinta, sama seperti bahasa, hanya akan indah bila ditaati aturannya. Dan mungkin, di situlah letak sejati qawā‘id al-‘isyq.
وَإِنْ لَمْ يُكْتَبْ لِهَذَا الْحُبِّ أَنْ يُقَالَ بِاللِّسَانِ، فَلْيَكْفِ أَنْ يَبْقَى مُتَّصِلًا فِي الْقَلْبِ، صَامِتًا وَلَكِنْ بَيِّنًا.
“Dan bila kelak cintaku tak sempat terucap dengan kata, biarlah ia hidup seperti dhomir muttashil—melekat erat dalam diam, sederhana, tapi jelas terasa.”
Penulis: Khoirunnisa S | Editor: Deré
