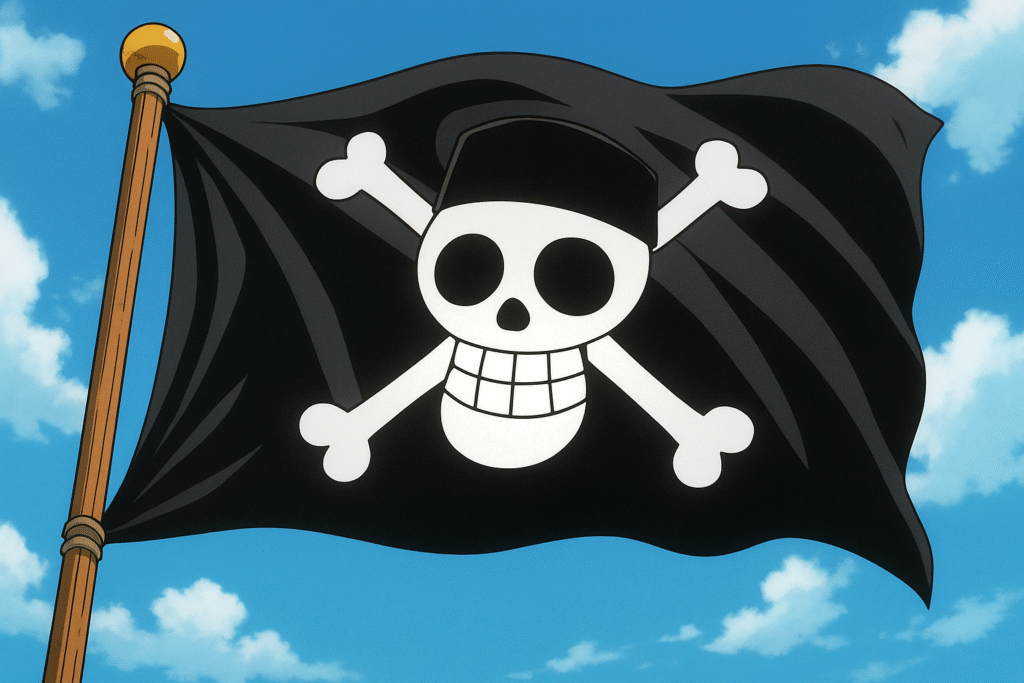
Belakangan ini, For You Page (FYP) kita dipenuhi dengan gambar Jolly Roger, sebutan bendera bajak laut dalam anime One Piece1. Kegaduhan ini bermuara dari statement tokoh publik yang menganggap simbol tersebut sebagai upaya pemecah belah bangsa. Memang, sudah menjadi tradisi bahwa sesuatu yang menggoyang citra pemerintah, jika berasal dari “dalam” akan dilabeli sebagai “oknum”, dan bila bersumber dari “luar” akan dicap sebagai “upaya adu domba”. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia begitu rentan terpecah belah karena terbentuk dari berbagai macam ras, etnis, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Menyatukannya menjadi Indonesia, bagi penulis sudah menjadi suatu keajaiban. Selain itu, manusia juga makhluk visual. Tidak heran jika yang lebih disorot hanya sebatas simbol, bukan esensi kenapa bendera One Piece itu bisa marak dikibarkan. Tak lebih, yaitu ekspresi kekecewaan terhadap stabilitas negara, yang mana jika diutarakan secara gamblang bisa berbuah teror kepala babi maupun UU ITE. Namun, kita tidak akan lebih jauh lagi dalam membahas fenomena unik ini. Dalam beberapa paragraf ke bawah, penulis akan membagikan pandangan pribadi terkait macam-macam sikap dalam merespons kondisi sosio-politik negara. Penulis membaginya menjadi tiga kategori, yaitu apatis, kritis, dan anarkis.
Politik itu najis, kotor, bahkan haram untuk dimasuki. Pernah mendengarnya? Seperti itu kiranya ekspresi yang timbul dari sikap apatis. Sikap ketika seorang individu ataukelompok tidak menunjukkan minat atau keterlibatan terhadap isu-isu sosial, politik, dan bahkan lingkungan sekitar, serta cenderung menutup diri darinya. Sikap ini bisa dikatakan pandangan tradisional yang berkembang di kalangan santri. Namun, hemat penulis, itu hanya pemahaman harfiah dari prinsip menjauhi kekuasaan. Senada dengan salah kaprah dalam konsep menjauhi hal duniawi yang dimaknai meninggalkan mencari maisyah (pendapatan finansial) secara mutlak, atau konsep zuhud dengan berpenampilan kumuh dan semrawut. Hal ini sering kali disandarkan pada gaya hidup para sufi dalam kajian tasawuf. Namun, apakah memang seperti itu? Dalam literatur yang kita kaji tiga kali seminggu bersama Gus Inan, karya ulama sufi Syaikh Abi Bakar Syatha ad-Dimyathi, Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Ashfiya’2, terdapat keterangan menarik terkait sikap ulama akhirat terhadap penguasa atau pemerintah.
ويكون منقبضا عن السلطان # ان لا يكون عليه يوما داخلا
Bait tersebut menjelaskan bahwa salah satu tanda ulama akhirat3 yaitu menjauhkan diri dari sultan (penguasa atau pemerintah sebuah wilayah), kecuali jika mendapati suatu kondisi yang mengharuskannya untuk memasuki hal tersebut (politik). Meskipun sikap tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ciri ulama akhirat, keberadaannya cukup relevan jika dinisbahkan kepada santri yang juga menyibukkan diri dalam menekuni ilmu akhirat (agama). Anjuran tersebut bukan tanpa sebab. Syaikh Abi Bakar Syatha menjelaskan bahwa ketika seseorang dekat dengan penguasa akan menimbulkan beberapa perilaku negatif, seperti: 1) bergelimangan harta penguasa hingga lupa akan nikmat dari Allah, 2) diam terhadap kemungkaran penguasa, 3) bermanis kata, berbohong, bahkan menjilat untuk menyenangkan penguasa, 4) serakah hingga memakan perkara haram. Namun, pada separuh bait yang akhir, sikap yang diambil berbalik 180 derajat. Bukan hanya mendekat, tetapi memasuki ranah pemerintahan adalah sebuah hal yang wajib. Alasan dan tujuannya ada pada bait setelahnya.
الا لنصح او لدفع مظالم # او لشفاعة في المراض فادخلا
Kita diharuskan masuk ke dunia politik untuk menjalankan beberapa misi. Tugas kita yaitu memberi nasihat kepada pemerintah, menolak kezalimannya, dan membantunya memperbaiki kebobrokan pemerintahan. Semua itu dilakukan dengan catatan kita tetap menjauhi ketamakan terhadap harta maupun kekuasaan, sampai pada masanya nasihat kita masuk ke hati penguasa, dan pertolongan kita diterima olehnya. Penjelasan ini menggambarkan sikap politik yang diambil Syaikh Abi Bakar Syatha sekaligus Syaikh Zainuddin Al-Malibari yaitu bukan apatis, tetapi kritis terhadap pemerintah. Menurut Paulo Freire, kesadaran kritis merupakan kemampuan seseorang untuk memahami realitas sosial, politik, dan ekonomi secara mendalam, kemudian bertindak secara sadar untuk mengubahnya. Bukan dengan egois membiarkan kezaliman penguasa dan kemungkaran merajalela.
Lantas, bagaimana dengan sikap anarkis? Apakah itu perilaku yang menciptakan kekacauan, huru-hara, kebrutalan, maupun kerusakan destruktif? Jika masih beranggapan bahwa anarkisme adalah tindakan tersebut, segeralah delete dari ingatan kalian. Sikap anarkis adalah menolak sistem pemerintahan otoriter dan mendukung masyarakat bebas, tanpa penindasan dan hierarki. Dalam sosiologi dan filsafat politik, anarkisme adalah paham yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hanya saja, prinsipnya dalam menolak hierarki sering kali melahirkan cita-cita penggantian negara dengan masyarakat tanpa negara. Hal ini yang mungkin kurang relevan untuk kita implementasikan sebagai seorang warga negara Indonesia. Namun, spirit dalam menjunjung keadilan dan menolak penindasan patut diadopsi.
Setelah penjelasan tiga sikap di atas, penulis tidak bermaksud untuk memetakkan maupun melabeli seorang santri dengan sebuah kategori. Munculnya tiga sikap tersebut pada dasarnya punya motivasi masing-masing. Kebebasan pembaca dalam memilih sikap politik tetap penulis utamakan. Akan tetapi, penulis mengajak pembaca, khususnya santri, untuk proaktif dalam ranah politik dan sosial. Menjadi kritis, tidak apatis, tidak pula sampai tahap anarkis. Kita bisa menjauhkan diri dari politik, tetapi bentuk diam kita tidak akan mengubah apa pun. Mungkin kebijakan pemerintah tidak berdampak langsung pada diri kita, tetapi bisa saja saudara kita di suatu daerah yang merasakannya. Mungkin juga, alam kita yang bersedih akan keserakahannya. Syaikh Abi Bakar Syatha sudah memaparkan dengan jelas bahwa sebaiknya kita tetap kritis terhadap pemerintah. Teringat pula seruan guru kita setiap kajian malam Selasa, Gus Muna, yang menekankan pentingnya prinsip urun (berkontribusi) dalam kehidupan bersosial, sekecil apa pun kontribusi tersebut.
Selagi korupsi masih menjadi budaya yang dinormalisasi, angka pengangguran dan kemiskinan tak segera diatasi, eksploitasi alam besar-besaran masih dihalalkan, sedangkan bendera anime lebih dipermasalahkan, maka pesan penulis: tetaplah skeptis dan kritis terhadap pemerintah, sebelum segala sisi dari hidup kita dipajaki oleh mereka. Bersikaplah kritis meskipun hanya berbentuk gerakan simbolis seperti mengibarkan bendera One Piece. Terkadang, ekspresi berwujud karya seni malah lebih worth it dalam menyuarakan kritik dan isu sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan, jika harus menduduki kursi pemerintahan, penulis menyarankan untuk mengikuti wejangan Kiai Anwar Sa’dullah Malang: berpolitiklah dengan politik kerakyatan yang berkebangsaan, bukan politik elitis dan kekuasaan. Seperti itu kiranya, wallahu a’lam.
Penulis: Muhammad Fatih | Editor: Nayla Sya
- One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda.
↩︎ - Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Ashfiya’ adalah sebuah kitab yang menyuguhkan interpretasi Tarekat secara komprehensif. Syaikh Abi Bakar Syatha ad-Dimyathi menghadirkan kitab ini sebagai komentar terhadap rangkaian bait tasawuf karangan Syaikh Zainuddin Al-Malibari yang berjudul Hidayatul Adzkiya’. (NU Online)
↩︎ - Ulama akhirat (ulama yang benar) adalah seorang yang berkomitmen pada ilmu pengetahuan, yang bermanfaat dan berorientasi pada ketaatan. Selain itu, ulama akhirat juga menjauhi sifat keduniawian dan menjaga ilmu dari perihal omong kosong maupun perdebatan tanpa faedah. (NU Online)
↩︎
